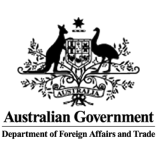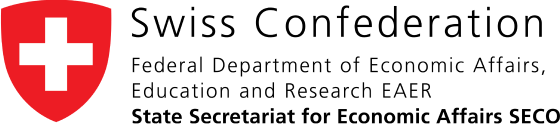Ultrafiltrasi, Teknologi Pengolahan Air Masa Depan?
2019-12-02 20:02:03 Dibaca : 777Oleh: Ris Sukarma
Dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Indonesia pada 13 Februari 2013, Dr. Ir. Djoko M. Hartono, SE, M. Eng. mengemukakan makin memburuknya kualitas air baku, melampaui nilai standar air baku air minum yang diijinkan. Selanjutnya dikatakan bahwa “bangunan instalasi pengolahan air minum yang ada sekarang menggunakan teknologi pengolahan air minum yang dibangun pada 15 sampai 40 tahun yang lalu yang dirancang berdasarkan kepada kondisi kualitas air baku pada saat itu yang hanya mempertimbangkan parameter kekeruhan saja.” Atau yang dikatakannya sebagai metoda konvensional.
Pada saat ini teknologi pengolahan air yang konvensional tampaknya tidak bisa lagi diandalkan untuk mengolah air baku yang semakin tercemar. Diperlukan unit pengolahan tambahan berupa teknologi adaptif, yang dapat berfungsi untuk mengurangi tingkat pencemaran. Unit tambahan ini tentu akan meningkatkan biaya produksi yang dampaknya akan meningkatkan harga jual air minum kepada masyarakat. Sebagaimana sudah kita ketahui, teknologi konvensional menggunakan proses penyaringan dengan saringan granular (umumnya pasir) dengan ukuran pori yang relatif besar. Diperlukan teknologi penyaringan dengan ukuran pori yang lebih kecil untuk bisa mengatasi memburuknya kualitas air baku.
Diantara teknologi pengolahan adaptif yang saat ini berkembang, nanofiltrasi banyak menarik perhatian para pakar. Nanofiltrasi adalah proses penyaringan melalui membran, digunakan untuk menyaring air dengan kandungan zat padat terlarut (TDS) yang rendah. Nanofiltrasi banyak digunakan dalam proses pengolahan makanan, tapi juga sudah mulai digunakan untuk menghasilkan air minum. Nanofiltrasi bekerja pada rentang antara ultrafiltrasi dan RO (reverse osmosis), dengan ukuran nominal pori membran sebesar 1 nanometer (satu perjuta millimeter). Meskipun efektif menghilangkan kontaminan dalam air baku, dan sering digunakan dalam proses desalinasi, kombinasi nanofiltrasi dan RO menghasilkan air yang tidak mengandung nutrien yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, sehingga proses ini dianggap kurang sesuai digunakan untuk pengolahan air minum. Bagi negara-negara berkembang, teknologi ini juga menimbulkan ketergantungan terhadap teknologi tinggi yang nota bene dimiliki negara-negara maju (Safer water, better health, WHO, 2008).
Pada ujung yang lain, mikrofiltrasi sudah lama digunakan dalam proses penyaringan. Dengan ukuran pori saringan antara 0,1 sampai 3 mikron (satu mikron sama dengan satu per seribu millimeter), mikrofiltrasi dapat menyaring bakteri penyebab penyakit perut. Proses mikrofiltrasi yang sudah lama dikenal, seperti dalam penggunaan saringan keramik. Teknologi ini dapat menghasilkan air yang bebas bakteri, tapi masih perlu dilapisi larutan perak koloid untuk menghilangkan virus. Saringan keramik pertama kali diperkenalkan oleh Henry Doulton tahun 1827. Teknologi ini kemudian dikembangkan sebagai teknologi tepat guna, antara lain oleh Potter for Peace dan Potter Without Border. Dengan teknologi tepat guna, saringan keramik dapat diproduksi oleh perajin keramik setempat dengan menggunakan bahan baku yang banyak terdapat di Indonesia, yaitu lempung. Karena kapasitas produksinya terbatas (1- 3.5 liter/jam), saringan keramik cocok sebagai pengolahan air skala rumah tangga (point-of-use treatment), apalagi pada saat dimana air PAM yang sampai dirumah pada umumnya belum dapat diminum langsung. Point-of-use treatment merupakan pendekatan yang disetujui dan didukung oleh WHO.
Ultrafiltrasi berada diantara mikrofiltrasi dan nanofiltrasi. Dengan rentang ukuran pori antara 0,01 sampai 0,1 mikron, ultrafiltrasi tampaknya teknologi yang cukup menjanjikan dalam teknologi pengolahan air di masa depan, paling tidak untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ultrafiltrasi adalah teknologi menengah yang dapat dikuasai oleh para ahli kita sendiri, dan ini sudah terbukti. Teknologi ultrafiltrasi dapat diterapkan pada proses pengolahan air skala kota dan kawasan.
Adalah Ir. Irman Djaya Dipl. SE, yang dengan ketekunannya telah berhasil mengembangkan dan menerapkan teknologi ultrafiltrasi pada instalasi pengolahan air minum. Salah satu hasil karyanya dapat dilihat di Kota Banjar (Jawa Barat), dimana proses ultrafiltrasi sudah diterapkan pada instalasi pengolahan air di kota itu (Buletin Cipta Karya, Januari 2013). Instalasi pengolahan yang dibangun dengan kapasitas produksi 50 liter/detik tersebut adalah instalasi pertama yang menerapkan teknologi ultrafiltrasi di Indonesia. Menurut Irman Djaya, air yang diolah melalui proses filtrasi harus melalui pengolahan pendahuluan terlebih dahulu untuk menurunkan kekeruhan menjadi dibawah 20 NTU. Setelah itu, air yang dihasilkan dapat langsung diminum tanpa pembubuhan disinfektan lagi. Investasi teknologi ultrafiltrasi ini tidak mahal, bahkan 20-25% lebih murah dari IPA konvensional, tapi belum termasuk pengolahan pendahuluan untuk menurunkan kekeruhan sampai dibawah 20 NTU. Sedangkan biaya operasinya sekitar 15-20% lebih murah dari IPA konvensional.
Efektivitas pengolahan dengan teknologi ultrafiltrasi ini mestinya sudah teruji, baik secara keilmuan maupun melalui hasil uji coba. Yang perlu dikaji lebih lanjut adalah keandalan sistem dalam kurun waktu tertentu. Misalnya menyangkut tentang usia teknis membran, efektivitas membran yang harus bekerja pada kondisi ekstrim tertentu (cuaca, perubahan kualitas air baku secara ekstrim dan mendadak), atau masalah operasional lainnya (kualifikasi dan pengalaman operator, ketersediaan suku cadang dan tenaga ahli).
Terlepas dari hal-hal yang disebutkan diatas, inovasi yang dikembangkan dalam pengolahan air melalui teknologi ultrafiltrasi perlu mendapat apresiasi. Pada saat dimana pencemaran sumber-sumber air permukaan meningkat, sedangkan instalasi pengolahan yang ada sudah tidak lagi mampu mengatasi peningkatan pencemaran, teknologi ultrafiltrasi bisa menjadi jawabannya.
Sumber: http://ris-sukarma.blogspot.com/2013/03/ultrafiltrasi-teknologi-pengolahan-air.html
Share On :